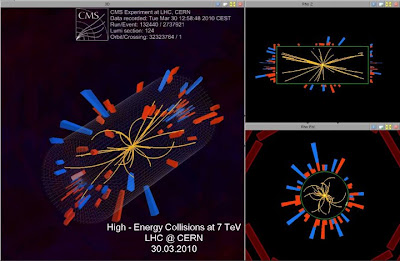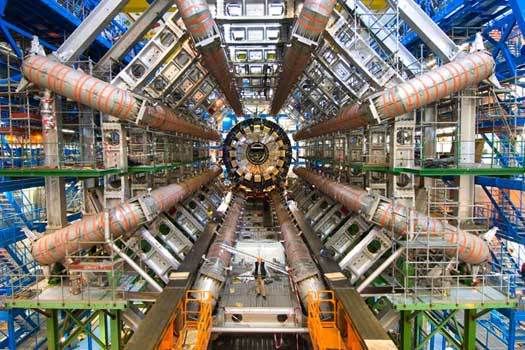Sebuah studi terbaru menunjukkan kalau laju pemanasan global dari penggandaan karbon dioksida atmosfer mungkin kurang dari perkiraan paling berani dari sebagian studi sebelumnya – dan, faktanya, mungkin kurang parah dibandingkan yang diproyeksi oleh laporan Panel Perubahan Iklim antar Pemerintah tahun 2007.
Sebuah studi terbaru menunjukkan kalau laju pemanasan global dari penggandaan karbon dioksida atmosfer mungkin kurang dari perkiraan paling berani dari sebagian studi sebelumnya – dan, faktanya, mungkin kurang parah dibandingkan yang diproyeksi oleh laporan Panel Perubahan Iklim antar Pemerintah tahun 2007.
Para pengarang studi ini, yang didanai oleh Program Paleoklimat Yayasan Sains Nasional AS dan diterbitkan online minggu ini dalam jurnal Science, menyebutkan kalau pemanasan global itu real dan kalau peningkatan CO2 atmosfer akan memiliki banyak pengaruh yang serius.
Walau begitu, proyeksi paling berani mengenai peningkatan suhu dari penggandaan CO2 tidak mungkin.
“Banyak studi sensitivitas iklim sebelumnya melihat ke masa lalu hanya dari 1850 hingga sekarang, dan tidak sepenuhnya mengintegrasi waktu paleoklimat, khususnya dalam skala global,” kata Andreas Schmittner, seorang peneliti Oregon State University dan penulis utama dalam artikel Science. “Ketika anda merekonstruksi suhu permukaan darat dan laut dari puncak zaman es terakhir 21 ribu tahun lalu – yang disebut Maksimum Glasial Terakhir – dan membandingkannya dengan simulasi model iklim periode tersebut, anda mendapatkan gambaran yang sangat berbeda.
“Jika kendala paleoklimat ini berlaku pada masa depan, seperti diramalkan oleh model kami, hasilnya menunjukkan kemungkinan kecil perubahan iklim ekstrim dibandingkan yang diduga sebelumnya,” tambah Schmittner.
Para ilmuan telah berjuang bertahun-tahun mencoba mengkuantifikasi sensitivitas iklim – yaitu bagaimana Bumi merespon pada peningkatan karbon dioksida atmosfer yang diproyeksikan. Laporan IPCC tahun 2007 memperkirakan kalau udara di dekat permukaan Bumi akan menghangat rata-rata 2 hingga 4.5 derajat Celsius dengan penggandaan CO2 atmosfer dari standar pra industri. Rata-rata atau nilai harapan peningkatan dalam perkiraan IPCC adalah 3,0 derajat; sebagian besar studi model iklim menggunakan penggandaan CO2 sebagai indeks dasar.
Beberapa penelitian sebelumnya mendaku pengaruhnya akan jauh lebih parah – hingga 10 derajat atau lebih dengan penggandaan CO2 – walaupun proyeksi ini mengakui rendahnya kemungkinan. Studi berdasarkan data hanya mundur hingga 1850 dipengaruhi oleh ketidakpastian besar dalam efek debu dan partikel kecil lainnya di udara yang memantulkan sinar matahari dan dapat mempengaruhi awan, yang disebut pemaksaan aerosol, atau dengan penyerapan panas oleh samudera, kata para peneliti.
Untuk menurunkan derajat ketidakpastian, Schmittner dan koleganya menggunakan sebuah model iklim dengan lebih banyak data dan menemukan kalau ada kendala yang mencegah tingginya sensitivitas iklim.
Para peneliti mengumpulkan rekonstruksi suhu permukaan laut dan darat dari Maksimum Glasial Terakhir dan menciptakan sebuah peta global suhu tersebut. Pada masa ini, CO2 atmosfer sekitar sepertiga kali lebih kurang dari Revolusi Industri, dan level metana dan nitrous oksida jauh lebih rendah. Karena sebagian besar lintang utara ditutupi es dan salju, permukaan laut lebih rendah, iklim lebih kering (kurang presipitasi), dan lebih banyak debu di udara.
Semua faktor ini, yang menyumbang pada pendinginan permukaan Bumi, dimasukkan dalam simulasi model iklim mereka.
Data baru ini mengubah penilaian model iklim dalam berbagai hal, kata Schmittner, asisten professor kampus ilmu bumi, samudera, dan atmosfer OSU. Rekonstruksi para peneliti pada suhu memiliki cakupan lebih luas dan menunjukkan pendinginan yang kurang pada masa Zaman Es daripada sebagian besar penelitian sebelumnya.
Model iklim sensitivitas tinggi – lebih dari 6 derajat – menunjukkan kalau level rendah CO2 atmosfer pada saat Maksimum Glasial Terakhir akan menghasilkan efek lari yang akan menyisakan Bumi seluruhnya tertutup es.
“Jelas, itu tidak terjadi,” kata Schmittner. “Walaupun Bumi kemudian ditutupi lebih banyak es dan salju daripada sekarang, lempeng es tidak membentang melebihi lintang 40 derajat, dan kawasan tropis dan sub tropis bebas es – kecuali daerah tinggi. Model sensitivitas tinggi ini melebih-lebihkan pendinginan.”
Di sisi lain, model dengan sensitivitas iklim rendah – kurang dari 1,3 derajat – meremehkan pendinginan hampir dimana saja di Maksimum Glasial Terakhir, kata para peneliti. Yang paling cocok, dengan derajat ketidakpastian jauh lebih rendah dari sebagian besar studi lainnya, menyarankan kalau sensitivitas iklim adalah sekitar 2,4 derajat.
Walau begitu, tingkat ketidakpastian dapat pula diremehkan karena simulasi model tidak mempertimbangkan ketidakpastian yang muncul dari bagaimana perubahan awan memantulkan sinar matahari, kata Schmittner.
Rekonstruksi suhu permukaan darat dan laut dari 21 ribu tahun lalu adalah tugas rumit yang melibatkan pemeriksaan inti es, lubang bor, fosil organism laut dan darat, endapan dasar laut, dan faktor-faktor lainnya. Inti endapan, misalnya, mengandung berbagai susunan biologis yang ditemukan pada berbagai rezim suhu dan dapat dipakai untuk mengetahui suhu masa lalu menggunakan analog pada kondisi samudera modern.
“Saat kami melihat pada data paleoklimat, saya terkejut dengan pendinginan samudera yang rendah,” kata Schmittner. “Secara rata-rata, samudera hanya sekitar dua derajat Celsius lebih dingin dari sekarang, namun planet ini sangat berbeda – lempeng es besar di Amerika Utara dan Eropa utara, lebih banyak es di laut dan salju, tetumbuhan yang berbeda, permukaan laut lebih rendah dan lebih banyak debu di udara.
“Itu menunjukkan kalau bahkan perubahan sangat kecil pada suhu permukaan samudera dapat memiliki dampak sangat besar, khususnya di daerah daratan pada lintang sedang dan tinggi,” tambahnya.
Schmittner mengatakan kalau bahan bakar fosil berkelanjutan dapat membawa pada pemanasan yang sama seperti pada permukaan laut di rekonstruksi yang terjadi antara Maksimum Glasial Terakhir dan sekarang.
“Karenanya, perubahan drastis di daratan dapat terjadi,” katanya. “Walau begitu, studi kami menunjukkan kalau kita masih punya cukup waktu untuk mencegah itu terjadi, bila kita berusaha mengubah arahnya dengan segera.”
Pengarang lainnya studi ini mencakup Peter Clark dan Alan Mix dari OSU; Nathan Urban, Princeton University; Jeremy Shakun, Harvard University; Natalie Mahowald, Cornell University; Patrick Bartlein, University of Oregon; dan Antoni Rosell-Mele, University of Barcelona.